Support by SAMUDRA PELAUT TRUST DESA
Bayangkan dunia tanpa chip. Tanpa prosesor, tak ada ponsel, tak ada internet, tak ada kecerdasan buatan. Chip semikonduktor adalah “minyak baru” abad ke-21, dan perebutan kendali atasnya kini menjadi rivalitas paling panas antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok. Jika dulu ketegangan hanya berkisar pada tarif dagang, kini konflik bergeser ke ranah teknologi, dengan semikonduktor, kecerdasan buatan, dan infrastruktur siber sebagai arena utama.
Ketegangan bermula sejak 2018, ketika Presiden Donald Trump melancarkan perang dagang dengan tarif tinggi terhadap barang-barang Tiongkok. Setahun kemudian, Huawei masuk daftar hitam AS dan kehilangan akses ke layanan Google serta pasokan chip global. Pada 2020, giliran Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC), produsen chip terbesar Tiongkok, dibatasi aksesnya ke teknologi mutakhir. Tahun 2022, Washington memperketat kontrol ekspor dengan tujuan utama: mencegah Beijing mendapatkan teknologi AI terbaru. Strategi ini disebut *freeze-in-place*, membekukan kapabilitas Tiongkok agar tidak melompat ke frontier berikutnya.
Namun, tekanan justru melahirkan perlawanan. Pada 2023, Huawei mengejutkan dunia dengan meluncurkan ponsel berchip 7 nanometer buatan lokal. Capaian itu membuktikan bahwa meski terhimpit embargo, Tiongkok mampu menapaki jalur kemandirian teknologi. Pada 2025, SMIC bahkan mulai menguji mesin litografi imersi ultraviolet dalam (DUV) buatan dalam negeri. Walau belum menyamai standar EUV yang dikuasai AS dan sekutunya, perkembangan ini menandai langkah besar dalam rantai pasok semikonduktor Tiongkok.
Di sisi lain, Nvidia menjadi simbol tarik-menarik antara kedua kekuatan. Setelah menyesuaikan diri dengan kontrol ekspor AS melalui chip versi terbatas H20 dan RTX Pro 6000D, perusahaan itu tetap dipukul telak. Pada Agustus 2024, regulator Tiongkok memerintahkan perusahaan domestik menghentikan pembelian chip H20 dengan alasan keamanan nasional. Beberapa bulan kemudian, larangan itu diperluas ke RTX Pro 6000D. Praktis, pintu Tiongkok tertutup bagi Nvidia, padahal pasar ini adalah yang terbesar kedua di dunia. Langkah itu diyakini muncul dari kepercayaan diri Beijing bahwa performa chip lokal sudah cukup untuk menggantikan produk asing.
Huawei menjadi ikon kebangkitan tersebut. Chip Ascend dan infrastruktur CloudMatrix terbaru menunjukkan performa yang, dalam beberapa metrik, mampu menyaingi sistem Nvidia. Caranya bukan dengan satu chip lebih unggul, melainkan dengan skala: menghubungkan lima kali lebih banyak prosesor untuk menutup kekurangan. Alibaba, Baidu, hingga startup seperti DeepSeek kini menyesuaikan model AI mereka agar kompatibel dengan chip lokal, membuktikan bahwa ekosistem digital Tiongkok sedang menuju kemandirian. Meski demikian, hambatan besar masih ada: kapasitas produksi masal belum mampu memenuhi kebutuhan domestik. Karena itu, pemerintah Beijing menargetkan pelipatgandaan output chip AI dalam waktu dekat.
Sementara Tiongkok semakin agresif, AS justru menunjukkan ambiguitas strategi. Di bawah Presiden Joe Biden, strategi utama adalah kontainment total—mencegah Tiongkok mendekati frontier teknologi dengan memperketat ekspor, memblokir Huawei, dan membatasi SMIC. Namun Donald Trump menempuh jalan berbeda. Ia melonggarkan lisensi ekspor chip H20 dengan alasan menjaga Tiongkok tetap “kecanduan” ekosistem Nvidia, sekaligus menjadikannya kartu tawar dalam negosiasi dagang. Kebijakan transaksional ini berseberangan dengan garis keras kubu keamanan nasional AS, yang menuntut pemisahan penuh rantai pasok. Akibatnya, Washington terjebak dalam dualisme: antara kontainment strategis dan pragmatisme bisnis.
Tiongkok memanfaatkan ambiguitas ini dengan mengembangkan instrumen non-teknologi. Mereka membatasi ekspor mineral kritis, membuka penyelidikan anti-monopoli terhadap perusahaan asing, dan memperketat regulasi data. Pasar domestik yang masif dijadikan alat tekanan, bukan sekadar ruang konsumsi. Dengan menutup akses Nvidia, Beijing tidak hanya melindungi produsen lokal, tetapi juga memaksa dunia menyesuaikan diri dengan prioritas politiknya.
Strategi ini diperkuat oleh dimensi siber. Laporan internasional dari lembaga keamanan AS dan sekutunya mengungkap operasi siber canggih dari kelompok *advanced persistent threat* yang diduga disponsori Beijing. Targetnya adalah infrastruktur kritis dunia: listrik, telekomunikasi, hingga data pemerintahan. Operasi itu bersifat jangka panjang, sabar, dan sistematis, dengan tujuan strategis—mencuri kekayaan intelektual, mengumpulkan intelijen, sekaligus menanam akses tersembunyi untuk melumpuhkan lawan jika konflik pecah. Dengan demikian, strategi chip dan strategi siber Tiongkok berjalan seiring: membangun kemandirian, sambil mempercepatnya melalui jalur asimetris.
Hasil akhirnya adalah fragmentasi teknologi global. Dunia bergerak ke arah dua blok yang berbeda: satu dipimpin AS dengan standar teknologi dan ekosistemnya, satu lagi dipimpin Tiongkok dengan sistem alternatif yang semakin matang. Rantai pasok menjadi lebih mahal dan rumit, standar jaringan serta desain chip kian tidak kompatibel, dan konflik siber pun berpotensi menjadi bagian rutin dari rivalitas geopolitik. Bagi perusahaan Barat seperti Nvidia, situasi ini menciptakan dilema: mereka harus mematuhi kontrol ekspor AS, sekaligus menghadapi larangan di pasar Tiongkok.
Kesimpulannya jelas: Tiongkok tidak lagi sekadar peserta dalam aturan main yang ditetapkan Barat. Kini mereka ikut menulis ulang aturan itu. Dari melarang chip Nvidia hingga membangun superkomputer AI berbasis prosesor lokal, dari litografi SMIC hingga infiltrasi digital terhadap infrastruktur global, strategi Beijing mengarah pada satu tujuan: kuasai teknologi, kuasai masa depan. Bagi Barat, tantangannya adalah merespons secara holistik—berinovasi lebih cepat, memperkuat aliansi, dan membangun ketahanan siber. Sebab di abad ke-21, perebutan kekuasaan tidak lagi ditentukan di ladang minyak atau jalur laut, melainkan pada chip, kecerdasan buatan, dan jaringan digital yang menopang kehidupan modern.

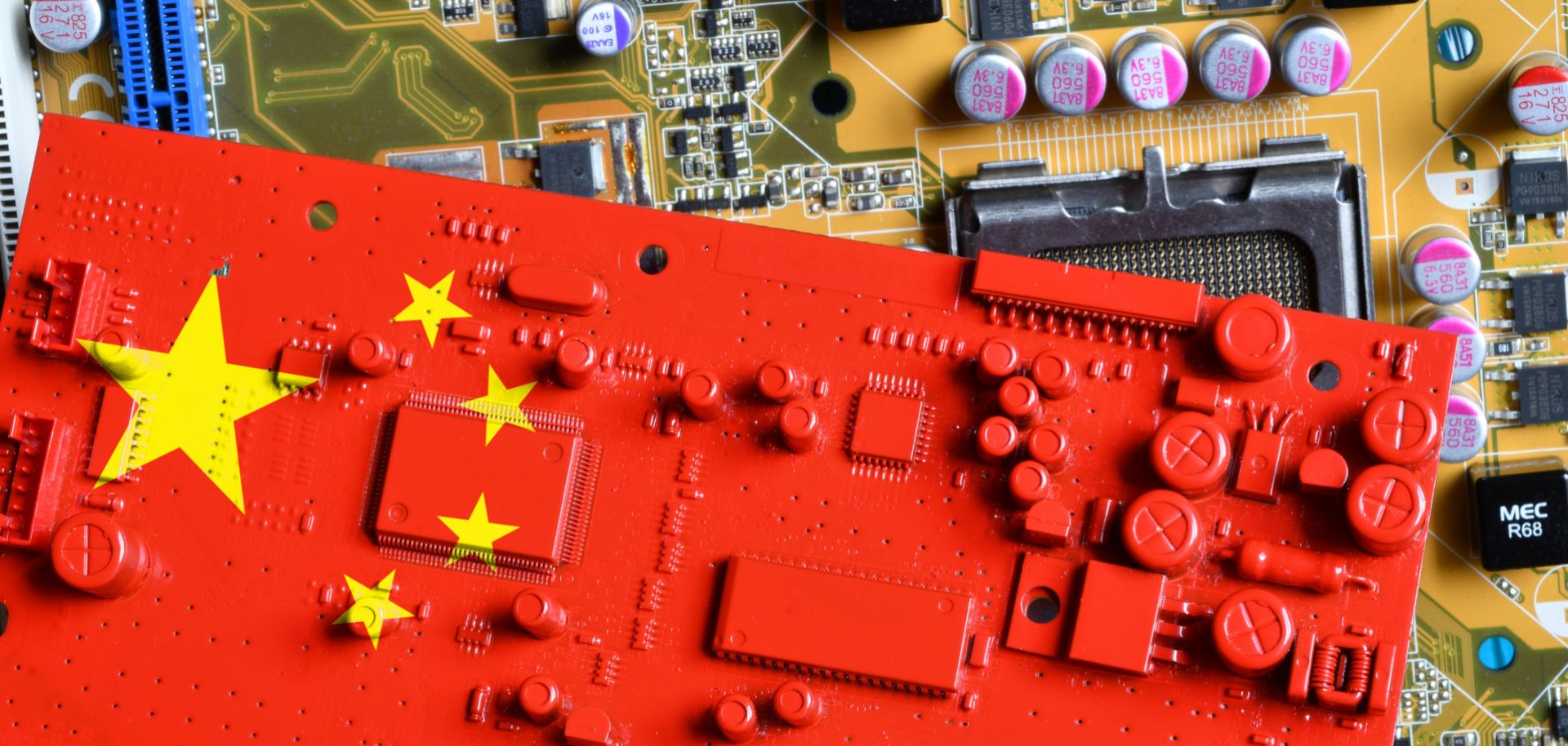






Komentar